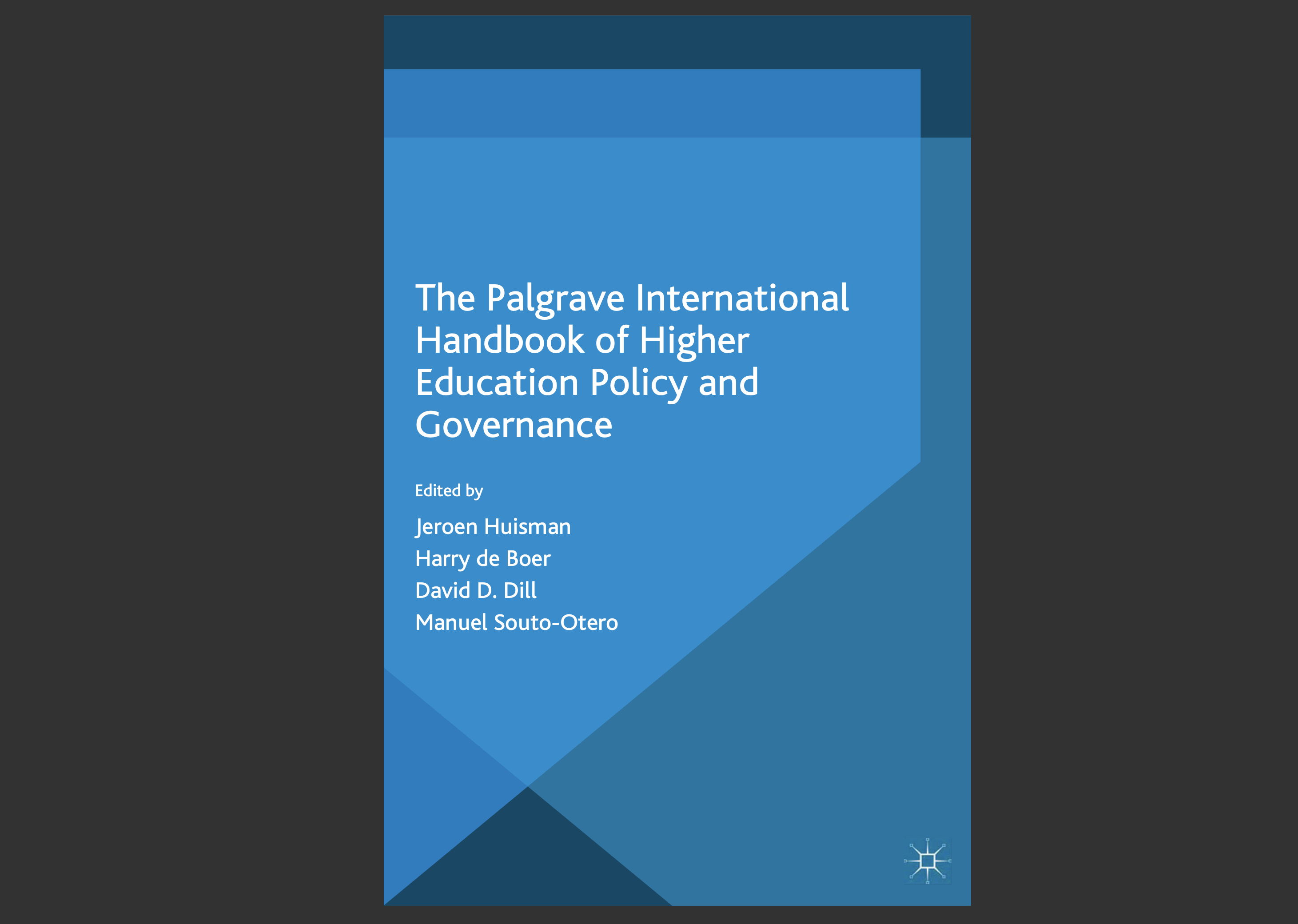
Sara Diogo, Teresa Carvalho and Alberto Amaral)*
Pendahuluan
Teori institusional biasanya mengacu pada sekelompok perspektif yang menafsirkan hubungan antara institusi dan perilaku manusia, dengan asumsi bahwa tidak hanya tindakan manusia (yaitu perilaku, persepsi, kekuasaan, preferensi kebijakan, proses pengambilan keputusan) yang membentuk institusi, namun hal ini juga dipengaruhi oleh institusi. oleh mereka. Lebih khusus lagi, institusionalisme berfokus pada kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan kelembagaannya, seperti norma, aturan, dan pemahaman tentang perilaku apa yang dapat diterima atau normal dan tidak dapat diubah dengan mudah dan/atau seketika (March dan Olsen, 1984 ; Meyer dan Rowan, 1977). Argumennya adalah bahwa organisasi menerima begitu saja aturan dan norma karena aturan dan norma tersebut tampak jelas atau alami. Kegagalan untuk bertindak sesuai dengan norma dan harapan dapat menyebabkan konflik dan anak haram. Perubahan yang terjadi pada bidang kelembagaan pendidikan tinggi (PT) dikatakan semakin menghambat lembaga pendidikan tinggi (PT). Mengingat hal ini, semakin relevan untuk menganalisis perkembangan teori institusionalis dan cara teori tersebut diadaptasi ke bidang pendidikan tinggi.
Karya Selznick (1948, 1957) dan Parsons (1956) biasanya dianggap sebagai pionir dalam studi organisasi. Para sarjana ini berteori tentang kekayaan dan pentingnya lingkungan kelembagaan bagi struktur dan proses organisasi: misalnya, bagaimana lembaga berfungsi untuk mengintegrasikan organisasi dalam masyarakat melalui aturan, kontrak, dan otoritas universal (Thornton dan Ocasio, 2008, hlm. 99–100 ). Sepanjang tahun 1970an dan 1980an, pendekatan baru terhadap analisis institusional muncul dengan Meyer dan Rowan (1977), Zucker (1977), DiMaggio dan Powell (1983) dan Meyer dan Scott (1983) yang menekankan peran budaya dan kognisi dalam analisis institusional. (Thornton dan Ocasio, 2008). Selain elemen teknis dan sumber daya, para institusionalis ini berpendapat bahwa organisasi harus mempertimbangkan lingkungan ‘kelembagaan’ (internal): fitur regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang menentukan ‘kesesuaian sosial’, yaitu mitos rasional, pengetahuan yang dilegitimasi oleh pendidikan. , profesi dan peraturan perundang-undangan sebagai pembentuk dan pemberi pengaruh praktik dan struktur organisasi (Powell, 2007).
Tata kelola modern sebagian besar terjadi di dalam dan melalui lembaga-lembaga, di bawah pengaruh aktor-aktor yang menggunakan kekuasaan dan memobilisasi sumber daya kelembagaan, hubungan dan perjuangan politik (Bell, 2002). Faktanya, teori (dan narasi) tata kelola mengacu pada teori kelembagaan untuk lebih memahami hubungan dan organisasi yang bergantung pada kekuasaan dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan serta dalam dinamika pengambilan keputusan. Lembaga juga dapat memainkan peran penting tidak hanya dalam mengurangi biaya transaksi dan informasi serta berbagai bentuk ketidakpastian pasar yang terkait, namun juga dalam membantu memantau dan menegakkan kontrak dan/atau perjanjian (Bell, 2002, hal. 3–5). Namun demikian, karena mempengaruhi dan membentuk dinamika kelembagaan tidak dapat menjelaskan seluruh fenomena kelembagaan dan preferensi para aktor, maka institusionalisme dianggap sebagai teori ‘kisaran menengah’ karena perubahan dapat berasal dari sumber lain. Misalnya, Thoenig (2012) menunjuk pada kekuatan struktural yang mempengaruhi kehidupan institusi, seperti globalisasi, agenda ekonomi dan politik internasional, dan tekanan terhadap struktur nasional. Misalnya, struktur tata kelola melihat lingkungan dalam kaitannya dengan strategi internal untuk beradaptasi atau meminimalkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi, misalnya, banyak perubahan terkini dalam HE dapat dilihat sebagai respons organisasi terhadap dinamika pasar (Ordorika , 2014). Faktor budaya, kapasitas kelembagaan, dan hubungan antar aktor juga merupakan faktor yang membentuk perilaku.
Di antara rangkaian teori kelembagaan, bab ini sebagian besar berfokus pada pendekatan institusionalisme baru1 terhadap analisis kelembagaan PT. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan kita untuk lebih memahami interaksi antara konteks kelembagaan (juga dikenal sebagai bidang organisasi) dan aktor dalam kebijakan pendidikan tinggi di tingkat organisasi dan nasional (Witte, 2006). Institusionalisme baru menolak keutamaan kausal dari efisiensi, berbeda dengan perspektif seperti ketergantungan sumber daya (Pfeffer dan Salancik, 1978), analisis biaya transaksi (Williamson, 1981) dan demografi/ekologi organisasi (Hannan dan Freeman, 1977), yang fokus pada efisiensi. pada proses pertukaran konkret di dalam dan antar organisasi (Lounsbury dan Ventresca, 2003).
Penelitian tentang pengaruh studi organisasi dalam kebijakan pendidikan tinggi dimulai dengan studi kasus Burton Clark (1970, 1972) mengenai perguruan tinggi terpilih di Amerika Serikat (Fumasoli dan Stensaker, 2013), dengan studi kasus Cohen, March dan Olsen (1972) yang terkenal tentang ‘tong sampah’. model’ pada proses pengambilan keputusan di universitas dan dengan deskripsi Cohen dan March (1974) tentang universitas sebagai ‘anarki terorganisir’. Seperti yang akan kita lihat nanti, institusionalisme telah berguna dalam beberapa domain di bidang pendidikan tinggi. Perubahan tata kelola kelembagaan; dalam praktik pengambilan keputusan dan pola kepemimpinan; dalam peran kepemimpinan akademis; dalam model pendanaan sektor ini; dan dalam tantangan yang dihadapi profesi akademis, munculnya manajerialisme, pelembagaan desain kebijakan dan proses implementasi, serta dampak (yang berbeda) terhadap fungsi Perguruan Tinggi dan otonomi kelembagaan telah menjadi topik penelitian utama yang dianalisis melalui lensa kelembagaan (Carvalho, 2014 ; Carvalho dan Santiago, 2010a; Fumasoli dan Stensaker, 2013; Veiga, 2010; Witte, 2006).
Perlu disebutkan bahwa konsep institusi tidak identik dengan organisasi (Amaral dan Magalhães, 2003; Scott, 2001, p. 48), meskipun dalam literatur sering terlihat penggunaan kata ‘organisasi’ dan ‘institusi’. secara bergantian. Namun, dalam institusionisme baru, institusi dipandang berbeda dari organisasi dalam arti bahwa seperangkat norma dan budaya yang membentuk sebuah institusi tidak hanya terkait dengan proses organisasi dalam sebuah organisasi (Scott, 2001) namun mencakup aktor-aktor institusional yang mempengaruhi. ‘ tindakan dan sebaliknya dengan cara yang tidak bisa dilakukan organisasi (March dan Olsen, 2005). Mengingat bahwa penggunaan teori kelembagaan di Perguruan Tinggi memungkinkan untuk menafsirkan dengan lebih baik perilaku Perguruan Tinggi, aktor-aktornya dan interaksi di antara keduanya, universitas dan/atau politeknik dipandang sebagai institusi dan bukan sebagai organisasi, dan oleh karena itu tidak terlalu fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan. manajemen, kontrol dan kesuksesan. Lebih lanjut, sebagaimana diklarifikasi oleh Marilena Chaui (1999), ‘Universitas sebagai praktik sosial “didasarkan pada pengakuan publik atas legitimasi dan atribusinya yang memberikan otonomi dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, yang disusun berdasarkan peraturan internalnya sendiri. , aturan, norma dan nilai pengakuan dan legitimasi” ‘ (dalam Amaral dan Magalhães, 2003, hal. 247). Sebagai institusi sosial, universitas modern mendapatkan legitimasinya tidak hanya dari gagasan bahwa pengetahuan bersifat otonom dari agama dan negara dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari ide-ide pendidikan, refleksi, kreasi dan kritik (Amaral dan Magalhães, 2003), namun juga dari institusional. aturan dan perilaku yang ‘diterima begitu saja’. Dapat dikatakan bahwa Perguruan Tinggi berkembang dan bertahan sebagai cara bagi masyarakat untuk melestarikan dan menyebarkan pengetahuan, terutama saat ini ketika mereka memiliki peran yang tidak diragukan lagi dalam penciptaan ekonomi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Perantara inilah yang memposisikan universitas sebagai institusi sosial. Meyer dan Rowan (1977) juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan fitur sentral bagi masyarakat sebagai sebuah institusi dan sekaligus merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tenaga kerja.
Dalam bab ini, diberikan tinjauan singkat tentang asal-usul dan perkembangan institusionalisme serta beberapa konsep dan gagasan dasar untuk lebih memahami bagaimana teori ini diterapkan dalam kebijakan dan tata kelola perguruan tinggi. Bagian berikut ini mengacu pada tiga pendekatan terhadap institusionalisme baru yang secara tradisional diklasifikasikan oleh Hall dan Taylor (1996) dan bagaimana beberapa penelitian di bidang HE menggunakan perspektif ini. Proses serupa digunakan pada bagian yang ditujukan untuk menjelaskan perubahan institusional dan isomorfisme. Bab ini dilanjutkan dengan diskusi tentang penggunaan teori institusional dalam penelitian HE. Kami menyimpulkan dengan beberapa komentar akhir (dan kritik), serta menunjukkan beberapa pertanyaan/topik untuk penelitian masa depan.
Tiga pendekatan terhadap institusionalisme baru
Bagi Hall dan Taylor (1996, hal. 936) terdapat banyak kebingungan mengenai pertanyaan seperti apa yang dijawab oleh institusionalisme baru. Mereka berpendapat bahwa kebingungan ini dapat diminimalkan dengan mengakui bahwa institusionalisme bukanlah sebuah kesatuan pemikiran, melainkan tiga pendekatan analitis yang berbeda namun saling melengkapi, ‘yang masing-masing menamakan dirinya “institusionalisme baru”. Ketiga aliran pemikiran ini adalah institusionalisme historis (komparatif), institusionalisme pilihan rasional (juga dikaitkan dengan institusionalisme ekonomi karena kesamaan kedua pendekatan) dan institusionalisme sosiologis (organisasi). Semuanya mencurahkan perhatiannya pada pemahaman tentang peran institusi dalam menentukan perilaku individu, meskipun mereka menjelaskan hubungan dan hasil dunia sosial, politik dan organisasi dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, konsep institusi memiliki arti yang berbeda dalam berbagai jenis pendekatan teoritis.
Menurut Mahoney dan Thelen (2010, hal. 7), ketiga institusionalisme ini menjelaskan apa yang menopang institusi dari waktu ke waktu sekaligus menjelaskan kasus-kasus di mana guncangan atau pergeseran eksogen mendorong perubahan kelembagaan. Dengan mengekstrapolasi analisis penulis, kita dapat menggabungkan ketiga alur pemikiran ini untuk lebih memahami mengapa sifat spesifik dari HEI memungkinkan mereka bertahan seiring berjalannya waktu dan bagaimana peristiwa eksternal mempengaruhi perubahan kelembagaan. Secara kasar, ketiga pandangan yang saling melengkapi ini memiliki konsepsi yang sama tentang institusi sebagai ciri kehidupan politik dan sosial yang relatif bertahan lama (Mahoney dan Thelen, 2010, hal. 4). Inilah sebabnya mengapa masuk akal untuk melihat Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi dan mempertimbangkan konsekuensi dari proses pelembagaan yang ekstensif dan intensif (Meyer et al., 2008). Dalam pemikiran kelembagaan, lingkungan merupakan situasi lokal – yang membentuk dan mendefinisikan entitas inti, tujuan dan hubungan – dan oleh karena itu pengaturan pendidikan tinggi lokal sangat bergantung pada institusi yang lebih luas (Meyer et al., 2008), seperti lembaga penjaminan mutu, pemerintah pusat. – lembaga pemerintah, organisasi internasional dan sebagainya. Oleh karena itu, melihat Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi memungkinkan kita untuk melihat naskah budaya dan peraturan organisasi yang dibangun dalam lingkungan global, internasional dan nasional yang membentuk ciri-ciri utama situasi lokal: ‘bersama dengan bidang disiplin ilmu dan peran akademisnya, Perguruan Tinggi adalah didefinisikan, diukur, dan diterapkan di setiap negara secara eksplisit dalam istilah global (Meyer et al., 2008, hal. 188).
Menurut para penganut aliran institusional sejarah, umur panjang universitas sebagai institusi tidak dibenarkan oleh fungsi ekonomi dan politik tertentu atau dibentuk oleh warisan sejarah atau perebutan kekuasaan tertentu, namun oleh keterkaitannya dengan perkembangan kemajuan sosial dan masyarakat pengetahuan (Hall dan Taylor , 1996). Institusionalisme historis berupaya menjelaskan institusi dengan mengacu pada masa lalu, dengan fokus pada fitur dan konvensi unik mereka (Bevir, 2009, hal. 110). Institusi merupakan bagian dari rantai sebab dan akibat yang memperhitungkan faktor-faktor seperti penyebaran gagasan dan pembangunan sosio-ekonomi. Bagi sebagian besar penganut paham institusional sejarah, institusi cenderung bergantung pada jalur atau bahkan ‘melekat’ (Fligstein, 2008).Institusi cenderung menolak perubahan karena hal tersebut melekat pada kepentingan aktor dan juga karena institusi terlibat dalam kerangka kognitif dan kebiasaan aktor. Ketergantungan jalur menjelaskan sifat dan kecepatan perubahan dan apakah perubahan tersebut berada pada kontinum yang sama dengan perkembangan sebelumnya atau apakah perubahan tersebut menyebabkan diskontinuitas. Menurut institusionalisme historis, tindakan aktual dan masa depan merupakan cerminan pengalaman dan perubahan radikal dalam administrasi publik hampir tidak terjadi. Faktanya, salah satu kritik terhadap institusionalisme historis adalah fokusnya pada kontinuitas pembangunan, sehingga menghambat kapasitasnya untuk menjelaskan inovasi institusional dan perubahan yang cepat (Hodgson, 2008, hlm. 4–5). Menarik juga pendapat Aspinwall dan Schneider (2000, hal. 30) yang berargumentasi bahwa label institusionalisme sejarah adalah ‘salah kaprah’ karena setiap fenomena sosial dapat diatribusikan pada pengaruh sejarah. Oleh karena itu, menjadi tugas peneliti untuk dapat membedakan antara pengaruh sejarah yang penting dan yang ‘tidak penting’.
Studi Johanna Witte (2006) mengenai penerapan struktur gelar Bologna di empat lingkungan nasional dan kelembagaan yang berbeda sebagian besar menggunakan institusionalisme historis untuk menganalisis respons kebijakan terhadap tantangan serupa. Dalam skenario ini, ia menyimpulkan bahwa argumen budaya dan sejarah tampaknya lebih kuat di Jerman dan Italia jika dibandingkan dengan Belanda, dan bahwa keberhasilan atau kelancaran implementasi perubahan di Perguruan Tinggi bergantung pada kesesuaian dan/atau ketergantungan jalur institusi.
Institusionalisme pilihan rasional bergantung pada teori pilihan rasional. Institusionalisme pilihan rasional mengasumsikan bahwa semua aktor adalah rasional, dan oleh karena itu setiap orang mempertimbangkan keputusannya dalam kaitannya dengan kegunaannya bagi dirinya sendiri. Para aktor berperilaku dengan cara yang murni utilitarian untuk memaksimalkan kepuasan atas preferensi mereka, dengan efisiensi sebagai faktor yang mengkondisikan pilihan. Institusi dan aktor jelas dapat dipisahkan (Hall dan Taylor, 1996). Memaksimalkan preferensi individu mungkin akan menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi masyarakat, yang jika berperilaku rasional, akan mengasumsikan perspektif yang berkaitan dengan kualitas. Jadi, menurut perspektif ini, institusi pemerintah dan pasar merupakan faktor penting yang menjelaskan mengapa beberapa negara mengembangkan perekonomian yang efisien dan negara lainnya tidak (Koelble, 1995, hal. 232). Pada gilirannya, perkembangan ekonomi atau skenario sebaliknya – misalnya krisis ekonomi – menentukan strategi pemerintah dan lembaga dalam menghadapi tekanan eksternal tersebut. Dengan demikian, institusi mampu mempengaruhi pilihan dan tindakan individu namun tidak mampu menentukannya (Koelble, 1995). Institusi berubah karena preferensi masyarakat juga berubah (Bell, 2002). Pandangan ini sangat berbeda dengan institusionalisme historis, yang memandang aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik berada di luar kendali mereka (Koelble, 1995, hal. 235).
Institusionalisme sosiologi tidak hanya mendefinisikan institusi secara luas, termasuk peraturan, prosedur dan norma, namun juga simbol-simbolnya. Pada gilirannya, perkembangan ekonomi atau skenario sebaliknya, misalnya krisis ekonomi, menentukan strategi pemerintah dan lembaga dalam menghadapi tekanan eksternal tersebut. March dan Olsen (1984) melihat institusi dari pandangan Weberian, sebagai konstruksi yang dirancang untuk memberikan imbalan dan sanksi serta menetapkan pedoman perilaku yang dapat diterima – melahirkan nilai meritokrasi dan mempromosikan gagasan mobilitas sosial (Koelble, 1995) . March dan Olsen (1984, 1989) berpendapat bahwa perilaku manusia dipandu dan dibentuk oleh logika kesesuaian yang membentuk perilaku dan pilihan selain maksimalisasi utilitas. Mereka menjelaskan bahwa individu merasakan kebutuhan untuk mengikuti aturan, yang menghubungkan identitas tertentu dengan situasi tertentu untuk memperoleh keterampilan pengetahuan diri pribadi, yang pada gilirannya akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kesesuaian mengacu pada dimensi kognitif dan etika, target dan aspirasi, dan hal ini memandu individu untuk menyesuaikan diri dengan suatu institusi.
Perbedaan penting antara aliran sosiologi dan aliran pilihan rasional terletak pada cara pengambilan keputusan. Ketika mengambil keputusan, para pelembagaan sosiologi tidak bertanya, ‘[Bagaimana] bagaimana saya memaksimalkan kepentingan saya dalam situasi ini?’ Mereka malah bertanya, ‘[Apa] tanggapan yang tepat terhadap situasi ini mengingat posisi dan tanggung jawab saya?’ (Koelble , 1995, hal.233). Dengan demikian, lebih dari sekedar memaksimalkan utilitas pemikiran, institusi dan seperangkat aturan perilaku dan perilaku memberikan legitimasi dan kesesuaian bagi aktor institusi (Koelble, 1995, hal. 232). Di dalam Perguruan Tinggi terdapat prosedur hukum, administratif dan profesional, yang memfasilitasi dan mengarahkan lembaga dan aktor untuk mendapatkan makna, otoritas dan legitimasi. Namun demikian, hubungan kekuasaan mengarah pada situasi di mana seringkali lebih penting untuk mewujudkan properti yang dilegitimasi secara eksogen dibandingkan beradaptasi dengan kemungkinan dan tuntutan lokal (Meyer et al., 2008, hal. 192). Misalnya, dalam kasus penelitian profiling, kepentingan pimpinan universitas mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pengambil kebijakan (Pietilä, 2014). Jika nilai-nilai dan tujuan para aktor berbeda pendapat, para pemimpin mungkin akan menanggapi permintaan eksternal secara simbolis untuk mempertahankan inti organisasi. Penting bagi organisasi untuk mencapai kesesuaian normatif antara nilai dan keyakinan dari usulan reformasi kebijakan dan identitas serta tradisi organisasi (Pietilä, 2014).
Juga sehubungan dengan perbedaan antara institusionalisme pilihan sosiologis dan rasional, Kaplan (2006) menunjukkan bahwa dampak kelembagaan terhadap proses pengambilan keputusan di Perguruan Tinggi dapat diungkapkan dalam berbagai cara.2 Misalnya, perebutan (politik) atas sumber daya kelembagaan dan strategi serta alokasi manfaat dan/atau sanksi ‘akan ditentukan oleh fitur struktural organisasi, hubungan organisasi dengan lingkungannya, dan lingkungan sosial di mana para pesertanya berada’ (2006, hal. 216).
Perubahan kelembagaan dan isomorfisme
Bagi kaum institusional, perubahan terjadi melalui pelembagaan bidang dan/atau sektor organisasi tertentu, yaitu sekumpulan organisasi yang, secara agregat, merupakan wilayah kehidupan kelembagaan yang diakui. Faktanya, teorisasi mengenai bidang organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983), sektor atau bidang tindakan strategis (Meyer dan Scott, 1983) inilah yang menjadikan institusionalisme baru menonjol di antara perspektif perilaku organisasi lainnya. Struktur dan konteks merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika mempelajari perilaku kolektif. Dengan memahami institusi sebagai entitas yang menyusun bidang-bidang dan membantu memandu para aktor melewati kekacauan di sekitar mereka, institusi menentukan siapa yang menduduki posisi apa di bidang tersebut, memberikan aturan dan struktur kognitif kepada masyarakat untuk menafsirkan tindakan orang lain, dan pedoman yang harus diikuti dalam kondisi tertentu. ketidakpastian (DiMaggio dan Powell, 1983; Meyer dan Scott, 1983). Pelembagaan terjadi ketika ‘(…) proses, kewajiban, atau aktualitas sosial mengambil status seperti aturan dalam pemikiran dan tindakan sosial’ (Meyer dan Rowan, 1977). Pada gilirannya, pelembagaan yang bersifat koersif kemungkinan besar akan mengakibatkan frustrasi para aktor, hilangnya identifikasi terhadap institusi tersebut, dan bahkan keterasingan (cf. Amaral, Jones dan Karseth, 2002; Välimaa, 2005; Diogo, 2014a).
Menurut Meyer dan Rowan (1985, hlm. 94–95) struktur formal suatu organisasi adalah mitos sosial. Lembaga menghindari kecaman sosial, meminimalkan tuntutan akuntabilitas eksternal, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dan mencoba meningkatkan kemungkinan mereka untuk bertahan hidup (Greenwood et al., 2008, hal. 4). Struktur formal dan simbolik mungkin hanya sekedar hiasan jendela dan tidak ditujukan untuk mengubah status quo organisasi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan aktor-aktor institusional dalam praktiknya (realitas) berbeda dengan apa yang tampak mereka lakukan (fasad) (Meyer dan Rowan, 1985, hal. 96). Bentuk dan praktik kelembagaan yang digunakan tidak dipilih karena lebih efektif, sebagaimana tersirat dalam pengertian rasionalitas. Bentuk kelembagaan berfungsi sebagai praktik budaya dibandingkan dengan mitos dan upacara yang terjadi di masyarakat dan yang digabungkan oleh organisasi, mendapatkan legitimasi, sumber daya, stabilitas, dan meningkatkan prospek kelangsungan hidup (Meyer dan Rowan, 1977, hal. 340). Dengan demikian, variasi dalam struktur organisasi juga mempengaruhi konten budaya yang dibawa dan disebarkan oleh Perguruan Tinggi: meskipun beberapa sistem Perguruan Tinggi tidak mendukung perubahan dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sistem lainnya lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih luas (Meyer et al., 2008).
DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi sebuah paradoks dalam perilaku organisasi: sejak sekelompok organisasi muncul sebagai sebuah lapangan, para aktor membuat organisasi mereka semakin serupa sambil mencoba mengubahnya. ‘Mengapa ada homogenitas yang begitu mengejutkan dalam bentuk organisasi dan? praktiknya?’ (DiMaggio dan Powell, 1983, hal. 147). Apa yang dapat menyebabkan organisasi, setelah menjadi sebuah institusi, mengadopsi serangkaian pola, karakteristik, dan perilaku spesifik yang umum, sehingga menjadikan organisasi tersebut semakin homogen? Dalam kondisi apa organisasi publik saling meniru dan menghindari inovasi (Thoenig, 2012)? Bahkan ketika organisasi mencoba untuk berubah dan mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja mereka, setelah beberapa waktu upaya tersebut tidak seimbang dengan tingkat keragaman yang ada dalam suatu bidang (DiMaggio dan Powell, 1983). Hal ini terjadi karena adanya strukturisasi bidang organisasi. Dalam jangka pendek, tekanan terhadap isomorfisme sangat kuat (Thoenig, 2012). Bagi DiMaggio dan Powell (1983), proses yang paling jelas menerjemahkan dimensi kognitif perilaku isomorfik adalah imitasi, yaitu proses mimesis, seperti dijelaskan di bawah. Seiring dengan semakin matangnya bidang-bidang tersebut, terdapat dorongan yang tidak dapat dielakkan menuju homogenisasi seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan besar yang menyebabkan institusi-institusi menjadi semakin serupa (Greenwood dkk., 2008, hal. 6). Institusi dan aktor-aktornya menghadapi ketidakpastian dengan meniru institusi lain yang mereka anggap sebagai model atau orang-orang sukses di bidang yang sama (Scott, 2001).
Pelembagaan terjadi melalui tiga bentuk isomorfisme kelembagaan, atau ‘mekanisme difusi’: isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif (DiMaggio dan Powell, 1983, hal. 150). Mekanisme-mekanisme ini mengurangi keberagaman yang sistematis, karena semuanya mengarah pada peningkatan kesamaan perilaku institusi. ‘Faktor koersif melibatkan tekanan politik dan kekuatan negara, yang memberikan pengawasan dan kontrol terhadap peraturan; faktor normatif bersumber dari kuatnya pengaruh profesi dan peran pendidikan; dan kekuatan-kekuatan mimesis yang berasal dari respons-respons yang lazim dan dianggap remeh terhadap keadaan-keadaan yang penuh ketidakpastian’ (Powell, 2007, hal. 2). Faktor kuat yang menyebabkan homogenitas struktur dan perilaku dalam sektor Perguruan Tinggi adalah kecenderungan untuk menekankan keunggulan penelitian ketika universitas intensif penelitian menjadi teladan yang ditiru oleh Perguruan Tinggi lainnya. Penekanan pada keunggulan penelitian dipercepat melalui evaluasi nasional dan kelembagaan, benchmarking, dan skema pendanaan (Pietilä, 2014). Hal ini sebagian besar terjadi melalui faktor koersif dan mimesis.
Ramirez (2012) juga menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat seseorang, organisasi, dan negara-bangsa mengambil jalur tertentu dan tidak mengambil jalur lainnya. Di Perguruan Tinggi, dapat ditanyakan mengapa beberapa tren dan reformasi pendidikan menyebar dan yang lainnya tidak. Bagaimana mereka melakukan perjalanan, dengan asumsi demikian? ‘Yang lokal memang penting, namun seberapa penting hal itu berbeda-beda tergantung ruang dan waktu’ (Ramirez, 2012, hal. 434). Memang benar, memahami waktu dan ruang adalah salah satu kunci untuk menghindari kesalahan paling umum dalam penelitian komparatif (pendidikan): dengan asumsi bahwa semua sistem pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sama dan dengan kecepatan yang sama (Nóvoa dan Yariv-Mashal, 2003). Institusionalisme telah menjadi kerangka kerja yang berguna untuk mempelajari difusi internasional struktur tata kelola perguruan tinggi (Whitley dan Gläser, 2014).
Scott (2001) lebih lanjut berpendapat bahwa institusi didasarkan pada tiga pilar berbeda – regulatif, normatif, dan budaya-kognitif, yang memberikan stabilitas dan makna pada perilaku sosial. Selain itu, masing-masing pilar Scott menawarkan alasan berbeda untuk legitimasi kelembagaan, baik berdasarkan sanksi hukum, wewenang moral, atau dukungan budaya (Powell, 2007). Menurut Scott (2001) setiap pilar memberikan dasar legitimasi. ‘Legitimasi bukanlah sebuah komoditas yang harus dimiliki atau ditukarkan, namun sebuah kondisi yang mencerminkan keselarasan budaya, dukungan normatif, atau kesesuaian dengan peraturan atau hukum yang relevan’ (2001, hal. 45).
Elemen regulatif mewakili peraturan dan batasan institusi yang mengkondisikan perilaku aktor: misalnya, proses regulasi, pemantauan dan pemberian sanksi terhadap aktivitas (Scott, 2001, hal. 35). Para ekonom dan sejarawan ekonomi melihat institusi-institusi terutama didasarkan pada pilar regulatif yang beroperasi melalui isomorfisme koersif. Keberadaan lingkungan hukum yang sama mempengaruhi banyak aspek Perguruan Tinggi, seperti perilaku, struktur dan tanggapan terhadap tekanan/beban eksternal. Isomorfisme koersif juga dapat muncul dari mekanisme regulasi yang lunak (misalnya modus operandi Komisi Eropa dalam bidang pembuatan kebijakan pendidikan3). Proses Bologna mencerminkan contoh penerapan dan penyebaran model pendidikan umum ke berbagai negara, mendorong konvergensi sistem pendidikan tinggi nasional (Veiga dan Amaral, 2012).
Pilar normatif mencakup nilai, norma, peran dan aturan normatif yang memperkenalkan dimensi preskriptif, evaluatif, dan wajib ke dalam kehidupan sosial (Scott, 2001, p. 37). Skema normatif mendorong kepatuhan terhadap kewajiban sosial. Isomorfisme normatif berasal dari profesionalisasi karena mengalami proses sosialisasi yang sama, dan norma perilaku menjadi serupa (DiMaggio dan Powell, 1983). Misalnya, perguruan tinggi perlu menghadapi inovasi, yang mungkin menantang model transmisi pengetahuan tradisional. Situasi seperti ini dapat mengarah pada bentuk penyampaian pengetahuan yang lebih beragam, atau, inovasi dapat mengarah pada tanggapan umum dari lembaga-lembaga di sektor yang sama dengan melihat seberapa sukses organisasi beroperasi (Meyer et al., 2008).
Pilar budaya-kognitif berhubungan dengan konsepsi bersama tentang aturan-aturan yang membentuk sifat realitas sosial dan kerangka yang melaluinya makna dibuat. Pada tingkat antar-organisasi, para ilmuwan sosial mengakui kehadiran naskah dan keyakinan bersama sebagai indikator skema budaya-kognitif.4 Elemen kognitif yang paling penting adalah aturan konstitutif (Scott, 2001), yang melibatkan penciptaan kategori dan tipifikasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada konstruksi sosial para aktor dan kepentingan (Scott, 2001, hal. 41). Pilar kognitif berkaitan dengan isomorfisme mimesis ketika organisasi dimotivasi oleh interpretasi mereka terhadap perilaku sukses pihak lain (Greenwood et al., 2008, hal. 7). Dengan demikian, hal ini dihasilkan dari kekuatan pasar kompetitif yang bertentangan dengan kesesuaian normatif, yang terjadi melalui ekspektasi sosial dan budaya yang kuat terhadap perilaku organisasi tertentu (Bess dan Dee, 2008, hlm. 142–143). Isomorfisme mimetik terjadi ketika lembaga-lembaga ‘meniru’ perilaku satu sama lain untuk menemukan solusi yang tidak menuntut investasi tinggi dan didorong oleh ketidakpastian. Ketiga pilar ini menyeimbangkan dinamika kelembagaan dan membantu kita memahami cara kerja teori kelembagaan dalam praktiknya.
Teori institusional dalam penelitian pendidikan tinggi
Bagian ini menganalisis mengapa institusionalisme organisasi merupakan landasan teori yang baik untuk studi HE, khususnya reformasi HE (Ferlie, Musselin dan Andresani, 2008, hal. 273). Antara lain, dengan menjelaskan struktur dan proses HE, institusionalisme membantu kita memahami transformasi politik dalam organisasi dan hubungan antara institusi dan pemerintah, serta dinamika internalnya (Gornitzka, 1999). Lebih khusus lagi, kontribusi utama institusionalisme (baru) ditemukan dalam interpretasi perilaku PT, pelaku PT, dan interaksi antara lingkungan internal dan eksternal.
Lingkungan di mana HEI beroperasi sering dikaitkan dengan gagasan sistem terbuka (Scott, 2001), yang menekankan ‘pentingnya konteks atau lingkungan yang lebih luas karena hal tersebut membatasi, membentuk, dan menembus organisasi’ (Scott, 2001, hal .xiv). Dari perspektif ini, Perguruan Tinggi dipandang sebagai organisasi yang kompleks, tertanam dalam berbagai lingkungan, menerima masukan dari dan menghasilkan keluaran untuk lingkungannya, yang harus ditanggapi oleh lembaga-lembaga tersebut. Dalam setiap institusi terdapat unit-unit independen yang terpisah dan/atau terikat dari lingkungannya sesuai dengan tingkat keterkaitannya yang longgar atau erat (Scott, 2001). Gagasan tentang universitas sebagai organisasi yang berpasangan secara longgar berupaya memberikan gambaran institusi yang lebih cair dan terdesentralisasi (Weick, 1976). Sistem terbuka dan sosial menghasilkan norma-norma sosial dan referensi kognitif (Thoenig, 2012). Dengan demikian, perubahan PT, dapat dijelaskan melalui proses interaksi antara institusi dan lingkungannya. Ketika ketegangan dan tekanan dinamis untuk perubahan tertanam dalam institusi, terdapat berbagai jenis perubahan institusional (Mahoney dan Thelen, 2010, hal. 15).
Setelah karya pionirnya pada penelitian HE dari perspektif studi organisasi, Clark mengembangkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mempelajari universitas kewirausahaan (1998, 2004). Ia menganjurkan agar universitas dibangun melalui kombinasi faktor struktural dan budaya yang memberi mereka identitas khas dan, secara bersamaan, mempertahankan kondisi perubahan yang stabil dan memadai dalam lingkungan yang terus berubah (Fumasoli dan Stensaker, 2013). Konteks kelembagaan didefinisikan sebagai pemahaman sosial yang tersebar luas yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rasional – mitos yang dirasionalisasi, sebagai ‘aturan, norma, dan ideologi masyarakat luas’ (Meyer dan Rowan, 1985, hal. 84). Hal ini mengatur perilaku dan memberikan peluang bagi agen dan perubahan (Thornton dan Ocasio, 2008, hal. 102). Konteks kelembagaan seringkali bersifat pluralistik dan tidak konsisten, dan tidak memberikan reaksi yang sama terhadap tekanan kelembagaan yang sama, namun hal ini bekerja dalam dua cara: keduanya memungkinkan dan membatasi kemungkinan dan peluang institusi dan aktor. Inilah sebabnya mengapa institusionalisme merupakan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis pendidikan tinggi secara konkrit, sebagai serangkaian organisasi, peran, interaksi dan transaksi ekonomi yang spesifik dan lokal (Meyer et al., 2008, hal. 187). Selain itu, selama dekade terakhir, institusionalisme telah menjadi salah satu pendekatan dominan dalam studi integrasi Eropa (Pollack, 2009; Souto-Otero, Fleckenstein dan Dacombe, 2008).
Perubahan dalam HE harus dipahami mengingat munculnya konteks reformasi sektor publik, yang dibingkai oleh neoliberalisme, di mana pemerintahan dikonseptualisasikan sebagai negara minimal. Alih-alih memborong negara, gerakan neoliberal ‘menciptakan pola-pola baru dalam pemberian layanan berdasarkan serangkaian organisasi kompleks yang berasal dari sektor publik, swasta, dan sukarela’ (Bevir, 2009, hal. 6). Penekanan yang lebih besar pada lembaga-lembaga informal membuat para pelembagaan semakin tertarik untuk mempelajari tidak hanya birokrasi formal namun juga jaringan kebijakan, sehingga menyimpulkan bahwa di bawah pemerintahan baru, negara tidak terlalu bergantung pada aturan dan lebih banyak bergantung pada manajemen tidak langsung. tentang negosiasi dan kepercayaan (2009, hal. 112). Dalam skenario ini dan menurut teori pilihan rasional, dengan tidak adanya/atau kurangnya pemerintahan, stabilitas norma-norma organisasi, kesepakatan dan pola peraturan (norma-norma yang longgar) diperkirakan akan menentukan perilaku individu. Dengan kata lain, dengan tidak adanya otoritas yang lebih tinggi atau agen penegak hukum, jaringan dan logika kesesuaian juga membantu memandu aktor-aktor institusional melampaui apa yang ditetapkan secara hukum/resmi.
Organisasi sektor publik, seperti HEI, dapat bertanggung jawab atas perubahan simbolis dan normatif karena mereka menyampaikan (berhasil atau tidak) citra dan referensi ke lembaga lain (yaitu semacam fasad kelembagaan). Perguruan tinggi tidak hanya menciptakan tekanan, namun mereka juga sangat rentan terhadap tekanan yang sama. Di HEI mana pun, aktor-aktor yang berbeda mengambil peran yang berbeda dan diharapkan menunjukkan perilaku yang berbeda. Namun demikian, setelah ditetapkan dengan jelas, aturan dan prosedur (misalnya kebiasaan, praktik, dan tradisi lama) masih tetap berlaku. Individu kemudian cenderung mengikuti rutinitas (lama), baik karena lebih mudah dan nyaman bagi mereka dan/atau karena menurut mereka inilah yang diharapkan dari mereka.
Institusionalisme (Baru) mendapat perhatian khusus dalam bidang penelitian PT sebagai alat untuk menganalisis restrukturisasi kelembagaan yang terjadi seiring dengan reformasi kebijakan publik pada tahun 1970an yang berdampak pada administrasi publik secara umum dan akibatnya terhadap PT. Sebelumnya, dengan konsolidasi sistem negara-bangsa pada pergantian abad ke-19, model pendidikan tinggi yang dilembagakan secara global meluas dan berubah. Oleh karena itu, institusionalisme mendapat pendukung sebagai teori yang berguna untuk menganalisis peran negara dalam reformasi sektor publik ketika dihadapkan pada perubahan tersebut (Gornitzka, 1999; Kaplan, 2006). Teori kelembagaan mencoba memberikan penjelasan mengapa HE di seluruh dunia mencerminkan model umum dan mengapa sistem HE, meskipun berada pada jalur yang berbeda, mencapai perluasan yang hampir universal (Meyer et al., 2008, hal. 197).
Penjelasan lain yang menjelaskan konvergensi terhadap model atau proses umum untuk ‘mengejar ketertinggalan’ negara dalam hal kinerja pendidikan terletak pada kombinasi ketergantungan jalur dan institusionalisme historis dengan institusionalisme sosiologis. Meskipun undang-undang yang disahkan oleh pemerintah memaksa sistem pendidikan tinggi nasional yang ‘terbelakang’ untuk ‘mengejar’ sistem pendidikan tinggi yang lebih maju (Nagel, Martens dan Windzio, 2010), baik di tingkat nasional maupun kelembagaan, ada kemungkinan untuk mengamati semakin banyak kesamaan dalam hal kebijakan, struktur dan cara berfungsi (misalnya Proses Bologna, perubahan tata kelola dan struktur manajemen). Proses difusi ini terjadi karena, antara lain, tekanan normatif yang diberikan kepada dan oleh para profesional, definisi tujuan bersama, dan penerapan praktik dan rutinitas serupa. Seperti yang telah kita lihat, institusionalisme baru memberikan semacam peta mental untuk menjelaskan persistensi/kontinuitas dan konvergensi perilaku-perilaku umum.
Pada tingkat makro, institusionalisme baru memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk menganalisis proses restrukturisasi dan destrukturisasi/de-institusionalisasi kelembagaan, serta mekanisme reproduksi dan produksi dalam sistem dan institusi pendidikan tinggi. Menjelaskan proses pelembagaan dan de-institusionalisasi, Carvalho dan Santiago (2010b) menunjukkan bahwa institusionalisasi baru memungkinkan kita untuk lebih memahami hasil yang dihasilkan dari proses-proses tersebut. Namun, mereka juga menarik perhatian pada fakta bahwa pendekatan teoritis yang membatasi diri pada hubungan lingkungan hidup mungkin mengabaikan analisis proses pelembagaan dan de-institusionalisasi yang diterapkan pada Perguruan Tinggi, serta membatasi analisis tentang bagaimana para akademisi menafsirkan dan menanggapi tekanan manajerialis di tingkat mikro-organisasi (2010b, hal. 166). Sebagaimana dicatat oleh penulis, ‘Jika respons strategis terhadap tekanan eksternal berbeda pada setiap institusi, respons internal mungkin juga akan berbeda’ (Carvalho dan Santiago, 2010b, hal. 166). Hal ini terjadi karena restrukturisasi kelembagaan terjadi pada dua tingkat. Hal ini pertama kali bermula dari inisiatif politik untuk membentuk kembali struktur, peran dan rutinitas Perguruan Tinggi dan budaya akademisnya. Kedua, hal ini muncul dalam prosedur untuk melegitimasi ‘lingkungan’ atau ‘tatanan’ budaya-kognitif baru, yang terikat erat dengan ideologi pasar (Carvalho dan Santiago, 2010b, hal. 165).
Setelah reformasi NPM, Brückmann dan Carvalho (2014) memanfaatkan institusionalisme untuk menganalisis proses reformasi HE di Portugal pada tahun 2007, dan lebih khusus lagi reorganisasi tata kelola dan struktur manajemen untuk menilai apakah hal ini menghasilkan keragaman model organisasi yang lebih besar. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun faktor-faktor yang bersifat memaksa serupa karena peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, terdapat kemungkinan untuk menemukan keragaman dalam respons kelembagaan. Yaitu, HEI dapat memilih jumlah total anggota Dewan Umum, jumlah anggota eksternal yang tergabung dalam Dewan Umum, ada atau tidaknya senat akademik, dan lain-lain.
Fumasoli dan Stensaker (2013) memberikan beberapa contoh studi HE yang menggambarkan munculnya beragam bentuk universitas. Bleiklie dan Kogan (2007)
menguraikan model pemangku kepentingan, yang mencerminkan bagaimana pergeseran nilai-nilai sosial mempunyai implikasi terhadap universitas. Secara paralel, peran kepemimpinan universitas yang baru muncul telah disoroti dengan melihat bagaimana rektorat dan dewan mengambil tindakan dalam kerangka tata kelola yang baru (Fumasoli dan Stensaker, 2013, hal. 481).
Singkatnya, institusionalisme baru telah menjadi kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan oleh penelitian Perguruan Tinggi untuk lebih memahami bagaimana ketegangan eksternal dan internal mempengaruhi perilaku para aktor Perguruan Tinggi dan apa yang mungkin (atau tidak) kita harapkan dari mereka dalam menjalankan peran mereka; bagaimana mereka merancang, menerapkan dan mengembangkan reformasi dan strategi nasional dan kelembagaan yang menargetkan pendidikan tinggi, dan bagaimana tata kelola kelembagaan dan praktik manajemen didefinisikan ulang untuk memenuhi tuntutan dan kemungkinan yang semakin meningkat.
Komentar terakhir
Untuk memahami bagaimana sistem dan institusi pendidikan tinggi beradaptasi, bagaimana hal ini dirasakan oleh masyarakat, oleh perwakilan atau otoritas administratif dan bagaimana pendidikan tinggi harus menghadapi perubahan eksternal (masih) merupakan isu yang relevan dalam penelitian pendidikan tinggi (Neave, 2012). Bagian sebelumnya menjelaskan mengapa teori kelembagaan merupakan alat untuk lebih memahami dinamika kelembagaan dan untuk mengekstrapolasi pelajaran dari perilaku kelembagaan dan hubungan kelembagaan. Namun, karena pentingnya teori ini dalam ilmu sosial dan kehidupan politik, maka sulit untuk mendekati topik, definisi, penelitian, dan metodologi teori institusional yang luas. Pada gilirannya, hal ini bervariasi sesuai dengan alur pemikiran spesifik yang digunakan untuk menggambarkan fenomena institusional.
Khususnya, institusionalisme pilihan rasional mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap reformasi besar yang terjadi baru-baru ini dalam manajemen sektor publik dan desain kelembagaan, yaitu reformasi tata kelola sejak tahun 1970an dan 1980an. Menurut Hall dan Taylor (1996, hal. 952), institusionalisme pilihan rasional telah menghasilkan ‘penjelasan paling elegan’ mengenai asal usul institusi dan penjelasan tentang alasan mengapa institusi yang ada terus ada dengan menganalisis fungsi dan manfaat yang diberikannya. Namun demikian, penulis juga mencatat bahwa pemikiran ini telah dikritik karena tidak memiliki penjelasan yang meyakinkan mengenai inefisiensi institusi dan terlalu menekankan efisiensi yang ditunjukkan oleh beberapa institusi (Hall dan Taylor, 1996). Saat mengambil keputusan, orang cenderung bertindak dengan cara yang diperhitungkan secara seimbang, memikirkan motivasi utama mereka (yang mungkin tidak rasional), dan kemudian berusaha memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin. Dalam pengertian ini, individu bertindak berdasarkan informasi yang terbatas. Pada tingkat hierarki kelembagaan tertinggi – yaitu manajemen puncak Perguruan Tinggi – perilaku dan keadaan berubah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, meskipun para pengambil keputusan di Perguruan Tinggi terlibat dalam ‘tugas besar’ dalam menghitung setiap aspek utilitas yang mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan/atau sumber daya untuk mencapai solusi optimal (Koelble, 1995, hal. 233). Oleh karena itu, mereka perlu mempersempit pilihan terbaik yang ada dengan menggunakan rasionalitas dan memilih strategi yang paling memuaskan dibandingkan strategi yang optimal (Simon, 1947). Siswa juga tidak berperilaku sebagai klien yang mendapat informasi sempurna.
Pada saat yang sama, HEI juga sangat bervariasi dalam hal mereka membangun identitas organisasi yang terpisah dan mampu menunjukkan independensi dari negara (Whitley dan Gläser, 2014). Landasan teori yang saling melengkapi perlu dirumuskan untuk membingkai perkembangan ini. Kami percaya bahwa adalah suatu kesalahan jika hanya berfokus pada satu bab institusionalisme baru dan mengisolasinya dari saudara-saudaranya ketika berfokus pada penelitian HE.
Kaplan (2006) mengingatkan kita akan pentingnya institusi dan aktor kunci dan/atau kelompok strategis. Institusi mewakili konteks di mana pemerintah mengambil keputusan mengenai kebijakan. Hal ini membuat hasil tertentu menjadi mungkin dan stabil dan membuat hasil lainnya menjadi tidak mungkin terjadi. Namun, jika lembaga-lembaga tersebut tetap mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, jika mereka mengendalikan dan menentukan hasil-hasilnya, maka mereka mungkin akan memberikan beberapa keuntungan kepada kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya: Lalu bagaimana hal ini diterjemahkan ke dalam kehidupan kelembagaan? Kelompok manakah yang dimaksud dan bagaimana dinamikanya bervariasi di Perguruan Tinggi dengan struktur tata kelola dan praktik manajemen yang berbeda? Dan, pada tingkat sistem, bagaimana tipe dan peraturan pemerintah yang berbeda dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengubah kebijakan ketika pemerintah berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada konseptualisasi dan formulasi proses pelembagaan. Kita tahu dari institusionalisme bahwa pelembagaan penuh suatu struktur kemungkinan besar bergantung pada efek gabungan dari resistensi yang relatif rendah dari kelompok-kelompok lawan. Pembalikan dari proses ini, yaitu de-institusionalisasi, kemungkinan akan memerlukan perubahan besar dalam lingkungan yang dapat menyebabkan konflik antara aktor-aktor yang kepentingannya bertentangan dengan aktor-aktor lain yang memiliki kerangka kognitif berbeda (Pietilä, 2014).
Kami percaya bahwa lebih banyak penelitian harus dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan penelitian mengenai proses pelembagaan (Tolbert dan Zucker, 1996, hal. 175). Sebagai pendekatan berbasis proses, pelembagaan hampir selalu diperlakukan sebagai keadaan kualitatif: struktur dilembagakan, atau tidak (Tolbert dan Zucker, 1996). Oleh karena itu, kami kurang memiliki pengetahuan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor penentu variasi tingkat pelembagaan, serta bagaimana variasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesamaan di antara sejumlah organisasi. Pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pelembagaan juga akan memperluas pemahaman tidak hanya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan, tingkat penerimaan reformasi dan kerja sama menurut kelompok kelembagaan yang berbeda (yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, fakultas, staf non-pengajar, dan mahasiswa) , tetapi juga pada hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi. Mengembangkan penelitian mengenai hal ini dapat menjadikan institusionalisme lebih berguna dalam studi dinamika perguruan tinggi, khususnya mengenai kerangka tata kelola dan implementasi kebijakan. Apalagi di era internasionalisasi yang semakin meningkat dalam HE, institusionalisme dapat menjelaskan kemungkinan alasan terjadinya ketegangan dan/atau kontradiksi antara tekanan lingkungan untuk menyesuaikan diri dan kebutuhan untuk mempertahankan unsur-unsur keragaman nasional. Pada akhirnya, teori kelembagaan telah membantu membingkai dan menciptakan keteraturan serta memberi makna pada berbagai metamorfosis sistem pendidikan tinggi dan lembaga-lembaganya.
Catatan
1. Istilah ‘institusionalisme baru’ diciptakan oleh March dan Olsen pada tahun 1984 untuk membedakannya dari pendekatan teori administrasi publik di Amerika Serikat dan ilmu administrasi di Eropa. Label ‘baru’ sebagian besar menunjukkan adanya ‘institusionalisme lama’ yang diperbarui sehubungan dengan cara institusi dilihat dan dipelajari dalam ilmu politik (March dan Olsen, 1984, hal. 738).
2. Hal yang menarik adalah Kaplan (2006, hal. 216) menyebut universitas sebagai ‘lembaga lunak’ yang bertentangan dengan lembaga keras yang menjadi fokus para ekonom dan ilmuwan politik yang tata kelolanya didasarkan pada aturan tertulis dan tersirat untuk mengatur interaksi.
daftar Bacaan
References
Amaral, A., Jones, G. and B. Karseth (eds) (2002) Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance (Dordrecht: Springer).
Amaral, A. and A. Magalhães (2003) ‘The triple crisis of the university and its reinvention’, Higher Education Policy, 16(2), 239–253.
Aspinwall, M. D. and G. Schneider (2000) ‘Same menu, separate tables: the institutionalist turn in political science and the study of European integration’, European Journal of Political Research, 38(1), 1–36.
Bell, S. (2002) ‘Institutionalism’, in J. Summers (ed) Government, Politics, Power and Policy in Australia (pp. 363–380) (Melbourne: Pearson Education Australia).
Bess, J. and J. Dee (2008) ‘The application of organizational theory to colleges and uni- versities’, in Understanding College and University Organization: Theories of Effective Policy and Practice VI (pp. 1–17) (Sterling, VA: Stylus Publishing).
Bevir, M. (2009) Key Concepts in Governance (Los Angeles: SAGE).
Bleiklie, I. and M. Kogan (2007) ‘Organization and governance of universities’, Higher
Education Policy, 20, 477–493.
Bruckmann, S. and T. Carvalho (2014) ‘The reform process of Portuguese higher edu-
cation institutions: from collegial to managerial governance’, Tertiary Education and
Management, 30(3), 193–206.
Carvalho, T. and R. Santiago (2010a) ‘Still academics after all’, Higher Education Policy, 23,
397–411.
Carvalho, T. and R. Santiago (2010b) ‘New public management and “middle manage-
ment”: how do deans influence institutional policies?’, in L. Meek, L. Goedegebuure, R. Santiago and T. Carvalho (eds) The Changing Dynamics of Higher Education Middle Management (pp. 165–196) (Dordrecht: Springer).
Carvalho, T. (2014) ‘Changing connections between professionalism and managerialism: a case study of nursing in Portugal’, Professions and Organization, 1(2), 1–15.
Chaui, M. (1999) ‘A universidade em ruínas’, in H. Trindade (ed) Universidade em ruiìnas na repuìblica dos professors (pp. 211–222) (Petrópolis: Editora Vozes).
Clark, B. (ed) (1970) The Distinctive College (Chicago: Aldine).
Clark, B. (1972) ‘The organizational saga in higher education’, Administrative Science
Quarterly, 17(2), 178–184.
Clark, B. (ed) (1998) Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Trans-
formation (New York: International Association of Universities Press/Pergamon: Elsevier
Science).
Clark, B. (2004) ‘Delineating the character of the entrepreneurial university’, Higher
Education Policy, 17(4), 355–370.
Cohen, M., March, J. and J. Olsen (1972) ‘A garbage can model of organizational choice’,
Administrative Science Quarterly, 17, 1–25.
Cohen, M. and J. March (1974) Leadership and Ambiguity: The American College President
(New York: McGraw-Hill).
DiMaggio, P. and W. Powell (1983) (eds) The New Institutionalism in Organizational Analysis
(Chicago: University of Chicago Press).
Diogo, S. (2014a) ‘Implementing the Bologna Process in Portugal and in Finland: national
and institutional realities in perspective’, Journal of the European Higher Education Area,
1(1), 35–54.
Ferlie, E., Musselin, C. and G. Andresani (2008) ‘The steering of higher education systems:
a public management perspective’, Higher Education, 56(3), 325–348.
Fligstein, N. (2008) ‘Fields, Power and Social Skill: A Critical Analysis of the New Institutionalisms’, Center for Culture, Organizations and Politics. UC Berkeley: Center for Culture, Organizations and Politics. Retrieved from: https://escholarship.org/uc/item/
89m770dv.
Fumasoli, T. and B. Stensaker (2013) ‘Organizational studies in higher education: a
reflection on historical themes and prospective trends’, Higher Education Policy, 26,
479–496.
Gornitzka, Å. (1999) ‘Governmental policies and organisational change’, Higher Education,
38(1), 5–29.
Greenwood, R. and C. Hinings (1993) ‘Understanding strategic change: the contribution
of archetypes’, The Academy of Management Journal, 36(5), 1052–1081.
Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K. and R. Suddaby (eds) (2008) ‘Introduction’, The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism (pp. 1–46) (London: SAGE Publications Ltd). Hall, P. and R. Taylor (1996) ‘Political science and the three new institutionalisms’,
Political Studies, 44(5), 936–957.
Hannan, T. and J. Freeman (1977) ‘The population ecology of organizations’, The
American Journal of Sociology, 82(5), 929–964.
Hodgson, G. (2008) ‘The emergence of the idea of institutions as repositories of knowl-
edge’, in A. Ebner and N. Beck (eds) The Institutions of the Market: Organizations, Social
Systems, and Governance (pp. 23–40) (Oxford: Oxford University Press).
Kaplan, G. (2006) ‘Institutions of academic governance and institutional theory: a frame- work for further research’, in J. C. Smart (ed) Higher Education: Handbook of Theory and
Research, Volume XXI (pp. 213–281) (Dordrecht: Springer).
Koelble, T. (1995) ‘The new institutionalism in political science and sociology’, Compara-
tive Politics, 27(2), 231–243.
Lounsbury, M. and M. Ventresca (2003) ‘The new structuralism in organizational theory’,
Organization, 10(3), 457–480.
Mahoney, J. and K. Thelen (eds) (2010) Explaining Institutional Change – Ambiguity, Agency,
and Power (Cambridge: Cambridge University Press).
Sara Diogo et al. 129
130 Concepts, Theories and Methods
March, J. and J. Olsen (eds) (1989) Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics (New York, NY: Free Press).
March, J. and J. Olsen (1984) ‘The new institutionalism: organizational factors in political life’, The American Political Science Review, 78(3), 734–749.
March, J. and J. Olsen (2005) ‘Elaborating the new institutionalism’, Working Paper, 11, http://www.arena.uio.no retrieved November 2014.
Meyer, J. and B. Rowan (1977) ‘Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony’, American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.
Meyer, J. and B. Rowan (1985) ‘The structure of educational organizations’, in J. Meyer, and R. Scott (eds) Organizational Environments: Rituals and Rationality (pp. 71–97) (Beverly Hills, CA: Sage).
Meyer, J. and R. Scott (1983) Organizational Environments (Beverly Hills, CA: Sage). Meyer, J., Ramirez, F., Frank, D. and E. Schofer (2008) ‘Higher education as an institu- tion’, in P. Gumport (ed) Sociology of Higher Education: Contributions and Their Contexts
(pp. 187–221) (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
Nagel, A., Martens, K. and M. Windzio (2010) ‘Introduction – education policy in trans-
formation’, in K. Martens, K. Nagel, M. Windzio and A. Weymann (eds) Transformation
of Education Policy (pp. 3–27) (Houndmills: Palgrave Macmillan).
Neave, G. (ed) (2012) The Evaluative State, Institutional Autonomy and Re-engineering Higher
Education in Western Europe. The Prince and His Pleasure (Basingstoke and New York:
Palgrave Macmillan).
Nóvoa, A. and T. Yariv-Mashal (2003) ‘Comparative research in education: a mode of
governance or a historical journey?’, Comparative Education, 39(4), 423–439.
Ordorika, I. (2014) ‘Governance and change in higher education: the debate between classical political sociology, new institutionalism and critical theories’, Bordon, 66(1),
107–121.
Souto-Otero, M., Fleckenstein, T. and R. Dacombe (2008) ‘Filling in the gaps: European
governance, the open method of coordination and the European commission’, Journal
of Education Policy, 23(3), 231–249.
Pietilä, M. (2014) ‘The many faces of research profiling: academic leaders’ conceptions of
research steering’, Higher Education, 67, 303–316.
Parsons, T. (1956) ‘Suggestions for a sociological approach to the theory of organizations’,
Administrative Science Quarterly, 1, 63–85.
Pfeffer, J. and G. Salancik (eds) (1978) The External Control of Organizations: A Resource
Dependence Perspective (New York: Harper & Row).
Pollack, M. (2009) ‘The new institutionalisms and European integration’, in A. Wiener
and T. Diez (eds) European Integration Theory (pp. 125–144) (Oxford: Oxford University
Press).
Powell, W. (2007) ‘The new institutionalism’, The International Encyclopedia of Organization
Studies (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications).
Ramirez, F. (2012) ‘The world society perspective: concepts, assumptions and strategies’,
Comparative Education, 48(4), 423–439.
Scott, R. (2001) Institutions and Organizations (Thousand Oaks, CA: Sage).
Selznick, P. (1948) ‘Foundations of the theory of organizations’, American Sociological
Review, 13(1), 25–35.
Selznick, P. (1957) Leadership in Administration: A Sociological Interpretation (Berkeley:
University of California Press).
Simon, R. A. (1947) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in
Administrative Organization (New York: The Macmillan Co).
Thoenig, J. C. (2012) ‘Institutional theories and public institutions: traditions and appropriateness’, in G. Peters and J. Pierre (eds) Handbook of Public Administration (pp. 127–138) (Thousand Oaks, CA: SAGE Knowledge).
Thornton, P. and W. Ocasio (2008) ‘Institutional logics’, in R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin and R. Suddaby (eds) The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism (pp. 99–129) (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd).
Tolbert, P. and L. Zucker (1996) ‘The institutionalization of institutional theory’, in S. Clegg, C. Hardy and W. Nord (eds) Handbook of Organization Studies (pp. 175–190) (London: SAGE).
Veiga, A. (2010) Bologna and the Institutionalisation of the European Higher Education Area, Doctoral Dissertation (Porto: University of Porto).
Veiga, A. and A. Amaral (2012) ‘Soft law and implementation problems of the Bologna process’, Educação, Sociedade e Culturas, 36, 121–140.
Välimaa, J. (2005) ‘Social dynamics of higher education reforms: the case of Finland’, in Å. Gornitzka, M. Kogan and A. Amaral (eds) Reform and Change in Higher Education. Analysing Policy Implementation (pp. 245–269) (Dordrecht: Springer).
Weick, K. (1976) ‘Educational organizations as loosely coupled systems’, Administrative Science Quarterly, 21(1), 1–19.
Whitley, R. and J. Gläser (eds) (2014) Organizational Transformation and Scientific Change: The Impact of Institutional Restructuring on Universities and Intellectual Innovation (Bingley: Emerald Group Publishing Limited).
Williamson, O. (1981) ‘The economics of organization: the transaction cost approach’, American Journal of Sociology, 87(3), 548–577.
Witte, J. (2006) Change of Degrees and Degrees of Change: Comparing Adaptations of European Higher Education Systems in the Context of the Bologna Process, Doctoral Dissertation (Twente: Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente).
Zucker, L. (1977) ‘The role of institutionalization in cultural persistence’, American Sociological Review, 42, 726–743.
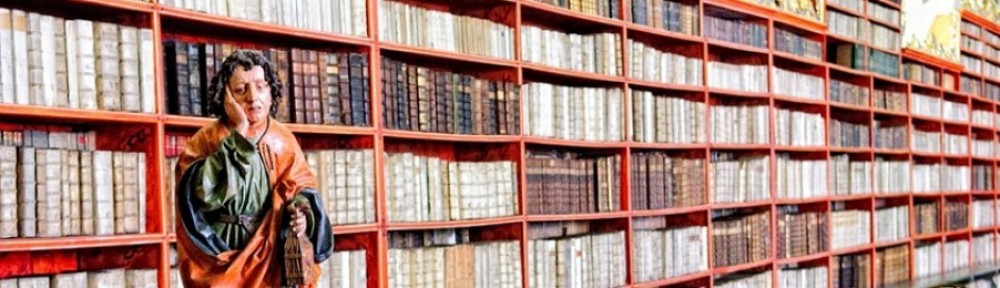
Leave a Reply